ABDURRAHMAN
WAHID “GUS DUR”
Tokoh
ini adalah tokoh Muslim
Indonesia
dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari
tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B. J. Habibie
setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Indonesia 1999
(Pemilu 1999). Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenannya dimulai
pada 20 Oktober
1999
dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun
2001. Tepat 23 Juli 2001,
kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah
mandatnya dicabut oleh MPR.
Tokoh
ini adalah Abdurrahman Wahid atau lebih banyak dikenal dengan nama Gus Dur, Gus
Dur adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama
dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB).
Abdurrahman Wahid atau yang akrab
dipanggil Gus Dur lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur dengan nama
lengkap Abdurrahman ad-dakhil putra pertama KH. Wahid Hasyim. Ayahnya adalah
menteri agama pertama Indonesia yang juga merupakan putra tokoh pendiri Nahdlatul
ulama, yaitu KH. Hasyim Asy’ari. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil.
"Addakhil" berarti "Sang Penakluk".[2] Kata "Addakhil" tidak
cukup dikenal dan diganti nama "Wahid", dan kemudian lebih dikenal
dengan panggilan Gus Dur.
"Gus" adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak
kiai yang berati "abang" atau "mas"
Waktu
kecil, Gus Dur sudah mulai menghafal sebagian isi Al-Quran dan banyak puisi
dalam bahasa arab. Ia memulai pendidikannya di sekolah rakyat, Jakarta. Setelah
itu ia melanjutkan sekolah ke SMEP di Giwangan Yogyakarta, bersamaan dengan
belajar bahasa arab di Pesantren Al-Munawir, Krapyak Yogyakarta di bawah
bimbingan KH. Ali Maksum, mantan Rais Am PBNU, dengan bertempat tinggal di
rumah KH Junaid, ulama tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Gus Dur secara terbuka
pernah menyatakan bahwa ia memiliki darah Tionghoa
Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia adalah keturunan dari Tan Kim Han yang
menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah
(Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.
Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri
Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V. Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian
seorang peneliti Perancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh
Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.
Pada tahun
1964, ia melanjutkan studinya ke Al-Azhar University Kairo Mesir dengan
mengambil jurusan Departement of Higher Islamic and Arabic
studies. Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementrian Agama untuk
belajar Studi Islam
di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir
pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab,
Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas
remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan
bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas
remedial.[9]
Abdurrahman
Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964, ia suka menonton film Eropa dan
Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola.
Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis
majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, ia berhasil lulus kelas remedial
Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965,
Gus Dur kecewa, ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak
metode belajar yang digunakan Universitas [10].
Di Mesir, Wahid
dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor
Jendral Suharto
menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai
bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan
untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan
kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan
menulis laporan.
Wahid mengalami
kegagalan di Mesir. Ia tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya
setelah G30S sangat mengganggu dirinya.
Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan
prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Wahid pindah ke Irak dan menikmati
lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar.
Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga
menulis majalah asosiasi tersebut.
Setelah
menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman
Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena
pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda, Wahid pergi
ke Jerman
dan Perancis
sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.
Jika dilacak, dari segi kultural, Gus
Dur melintasi tiga model lapisan budaya. Pertama, kultur dunia pesantren
yang sangat hirarkis, penuh dengan etika yang serba formal, dan apreciate
dengan budaya lokal. Kedua, budaya timur tengah yang terbuka dan keras;
dan ketiga, lapisan budaya barat yang liberal, rasional dan sekuler.
Semua lapisan kultural itu tampaknya terinternalisasi dalam pribadi Gus Dur
mebentuk sinergi. Hampir tidak ada yang secara dominan berpengaruh membentuk
pribadi Gus Dur. Ia selalu berdialog dengan semua watak budaya tersebut. Dan
inilah barangkali anasir yang menyebabkan Gus Dur selalu kelihatan dinamis dan
tidak segera mudah dipahami, alias kontroversi.
PEMIKIRAN SERTA GAGASAN ABDURRAHMAN WAHID
Abdurrahman Wahid
adalah tokoh besar yang tidak saja pernah memimpin organisasi keagamaan
terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, selama tiga periode berturut-turut,
sejak 1984-1999, tetapi juga seorang negarawan, pernah menjadi Presiden RI, dan
seorang kampium dalam memperjuangkan demokratisasi dan toleransi keagamaan di
Indonesia. Komitmen Abdurrahman Wahid terhadap demokrasi, pluralisme, dan hak
asasi manusia tidak diragukan lagi. Bahkan, Abdurrahman Wahid banyak
menggantungkan harapannya pada demokrasi.
Jika diperhatikan
pemikiran politik Abdurrahman Wahid senantiasa didasarkan pada sisi politik
Indonesia yang demokratis, sekular dan nasionalis. Bagi Gus Dur, sekularisasi
merupakan langkah pertama ke arah masyarakat demokratis yang hanya bisa
dibangun secara independen dari demokrasi politik yang sejati. Salah satu
keyakinannya adalah apabila Indonesia benar-benar akan menjadi civil
society yang demokratis, maka aspirasi politik masyarakat tidak boleh
disalurkan melalui agama. Bahkan, dalam amatannya, keterlibatan
kelompok-kelompok agama ke dalam politik praktis secara tak terelakkan akan
menimbulkan ketegangan-ketegangan sektarian dan polarisasi yang cukup tajam
antar berbagai gerakan Islam.
Abdurahman
Wahid lebih sering menggunakan ideologi nasional Pancasila ketimbang Islam
dalam melegitimasi partispasi politiknya. Abdurraham Wahid menganggap Pancasila
sebagai kompromi politik yang memungkinkan semua orang Indonesia hidup
bersama-sama dalam sebuah negara kesatuan nasional Indonesia. Menurutnya, tanpa
Pancasila, Indonesia akan berhenti sebagai negara.
Telah lama ia
berpendapat bahwa umat harus berpegang pada Pancasila. Ia memahami Pancasila
sebagai syarat bagi demokratisasi dan perkembangan Islam spiritual yang sehat
dalam konteks nasional. Di matanya, Indonesia adalah sebuah negara yang
didasarkan pada konsensus dan kompromi, dan kompromi itu inheren dalam
Pancasila. Dengan penuh keyakinan, Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa
pemerintahan yang berideologi Pancasila, termasuk negara damai (dar
al-shulh) yang harus dipertahankan. Menurutnya, hal ini adalah cara yang
paling realistik secara politik jika dilihat dari pluralitas agama di
Indonesia.
Lebih jauh,
bagi Abdurrahman Wahid, hal ini sepenuhnya konsisten dengan doktrin keagamaan
Islam yang tidak memiliki perintah mutlak untuk mendirikan negara Islam. Islam,
tandas Abdurrahman Wahid tidak mengenal konsep pemerintahan yang definitif.
Dalam persoalan yang paling pokok, misalnya suksesi kekuasaan, ternyata Islam
tidak konsisten; terkadang memakai istikhlâf, bai’at dan ahl
al-hall wa al-‘aqdi (sistem formatur). Padahal, dalam pandangan
Abdurrahman Wahid, soal suksesi adalah soal yang cukup urgen dalam masalah
kenegaraan. “Kalau memang Islam punya konsep, tentu tidak terjadi demikian”.
Tidak adanya
bentuk baku sebuah negara dan proses pemindahan kekuasaan dalam bentuk baku
yang ditinggalkan Rasulullah, baik melalui ayat al-Qur`an maupun al-Hadits,
membuat perubahan historis atas bangunan negara yang ada menjadi tidak
terelakkan dan tercegah lagi. Dengan demikian, maka kesepakatan akan bentuk
negara tidak bisa lagi dilandaskan pada dalil naqli, melainkan pada
kebutuhan masyarakat pada suatu waktu.
Menurut tokoh
kelahiran Jombang, Inilah yang menyebabkan mengapa hanya sedikit sekali Islam
berbicara tentang bentuk negara. Menurutnya, Islam memang sengaja tidak
mengatur konsep kenegaraan. Yang ada dalam Islam hanyalah komunitas agama (kuntum
khaira ummatin ukhrijat li al-nâs). Jadi, yang ada khaira ummatin bukan
khaira dawlatin, khaira jumhûriyatin, apalagi khaira
mamlakatin, kilahnya.
Gus Dur juga
menyatakan bahwa, para teoritisi politik yang besar dalam Islam bukanlah
mencari pola idealisasi bentuk kenegaraan yang islami, melainkan
justru menekankan penggunaan bentuk kenegaraan yang sudah ada. Dalam perspektif
ahl al-sunnah wa al-jamâ’ah, pemerintahan ditilik dan dinilai dari
segi fungsionalnya, bukan dari norma formal eksistensinya, negara Islam atau
bukan. Selama kaum Muslimin dapat menyelenggarakan kehidupan beragama mereka
secara penuh, maka konteks pemerintahannya tidak lagi menjadi pusat
pemikirannya. Biarkan setiap warga negara menjalankan ajaran agamanya, tanpa
intervensi negara. Dan biarkan pula,
setiap warga negara menentukan sendiri agama yang hendak dianutnya, tanpa
campur tangan pihak manapun.
Adapun
yang mendasari pemikiran Abdurrahman Wahid yaitu, bagaimana mengkombinasikan
kesalehan Islam dengan apa yang disebutnya komitmen kemanusiaan. Menurut lelaki
kelahiran 4 Agusuts 1940 ini, nilai itu bisa digunakan sebagai dasar bagi
penyelesaian tuntas persoalan utama kiprah politik umat, yakni posisi komunitas
Islam pada sebuah masyarakat modern dan pluralistik Indonesia. Humanitarianisme
Islam pada intinya menghargai sikap toleran dan memiliki kepedulian yang kuat
terhadap kerukunan sosial. Dari kedua elemen asasi inilah sebuah modus
keberadaan politik komunitas Islam negeri ini harus diupayakan.
Cita ideal yang diperjuangkan Abdurrahman
Wahid secara konsisten adalah komitmen terhadap sebuah tatanan politik nasional
yang dihasilkan oleh proklamasi kemerdekaan. Bahwa, semua warga negara memiliki
derajat yang sama tanpa memandang asal-usul agama, ras, etnis, bahasa dan jenis
kelamin. Konsekuensinya, politik umat Islam di Indonesia pun terikat dengan
komitmen tersebut. Segala bentuk eksklusifisme, sektarianisme, dan
primordialisme politik harus dijauhi. Termasuk disini adalah pemberlakukan
ajaran melalui negara dan hukum formal, demikian pula ide proporsionalitas
dalam perwakilan di lembaga-lembaga negara. Sebab, tuntutan-tuntutan semacam
ini jelas berwajah sektarian dan berlawanan dengan asas kesetaraan bagi warga
negara.
Pandangan ini
memiliki implikasi yang fundamental dalam konstelasi pemikiran politik Islam di
Indonesia, bahkan di dunia Islam umumnya. Pemikiran Abdurrahman Wahid ini
dipandang lebih radikal ketimbang pandangan politik Nurcholish Madjid yang
sudah dikatakan liberal. Akar modernisme Islam masih cukup kuat berkecambah
dalam pemikiran Nurcholish sehingga jika disimak dengan seksama ide pembentukan
sebuah masyarakat Islam masih diterimanya, paling kurang sebagai sebuah
masyarakat yang dibayangkan (immagined community). Dalam hal ini,
tentu saja, wawasan kebangsaan dan kapasitas toleransi yang tinggi terhadap
yang lain akan disyaratkan. Konsesi semacam itu pasti akan ditolak oleh
Abdurrahman Wahid sebab ia masih belum bergerak jauh dari pemahaman eksklusif.
Oleh karenanya, pemahaman ini tidak mampu menjamin terhapusnya hasrat dan
ambisi sektarian dalam batang tubuh umat. Dalam soal komitmen terhadap asas
kesetaraan ini, umat Islam harus benar-benar total. Karena tanpa itu,
kecurigaan dari luar dan sikap-sikap sektarian dari dalam tak mungkin bisa
dihapuskan.
Abdurrahman Wahid
sepenuhnya berpegang pada gagasan negara sekular yang memposisikan warga negara
yang berasal latar belakang berbagai agama memiliki hak-hak yang sama. Ia
dengan lantang menolak konsep “riddah” seperti yang tercantum dalam
sejumlah literatur fikih konvensional. Ia dengan gigih menentang setiap upaya
untuk memasukkan ketetapan hukum Islam ke dalam kitab undang-undang hukum
pidana di Indonesia. Bahkan, ia menyebut penerapan hukum pidana Islam di
Malaysia merupakan kegairahan untuk “kembali ke zaman kegelapan”.
Gagasan
kontroversial seperti ini agaknya secara sadar dimunculkan oleh Abdurrahman
Wahid agar tidak terjadi diskriminasi dan penomorduaan sekelompok anggota warga
bangsa di bumi Indonesia yang plural (ta’addudy) ini. Sebab, menurut
keyakinannya, diskriminasi apalagi hegemoni terhadap sekelompok warga negara
secara telanjang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang tanpa
lelah diperjuangkannya. Baginya, demokrasi adalah salah satu nilai fundamental
yang ada dalam Islam. Yang penting, menurut Abdurrahman Wahid, adalah
memperjuangkan nilai-nilai Islam, bukan universum formalistiknya. Dengan
memperjuangkan nilai-nilai yang ada dalam Islam, maka Abdurrahman Wahid bisa
mengatakan bahwa dia sedang memperjuangkan Islam. Di mata Abdurrahman Wahid,
Islam hanya dilihat sebagai sumber inspirasi-motivasi, landasan etik-moral,
bukan sebagai sistem sosial dan politik yang berlaku secara keseluruhan. Dengan
kata lain, Islam tidak dibaca dari sudut verbatim doktrinalnya, tetapi coba
ditangkap spirit dan rohnya. Islam dalam maknanya yang legal formal tidak bisa
dijadikan sebagai ideologi alternatif bagi cetak biru negara bangsa Indonesia.
Islam merupakan faktor pelengkap di antara spektrum yang lebih luas dari
faktor-faktor lain dalam kehidupan bangsa. Walhasil, visi Abdurrahman Wahid
tentang Indonesia masa depan adalah sebuah Indonesia yang demokratis, misalnya
adanya kedudukan yang sama bagi semua warga negara dari berbagai latar belakang
agama dan etnis manapun; mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
SUMBER
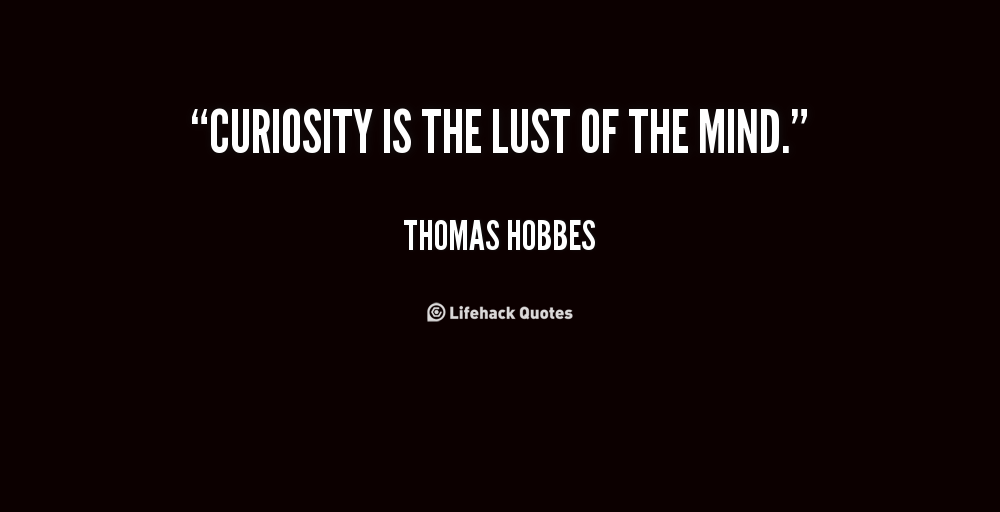










0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar dengan sepuasnya, dipersilahkan menggunakan kata kasar jika diperlukan, tapi saya yakin orang yang bermoral tidak akan menggunakan kata-kata yang kasar, khususnya untuk menghina tanpa dasar logika yang dapat diterima dengan nalar.